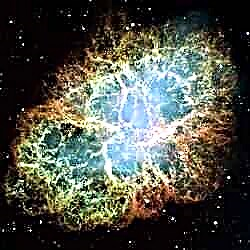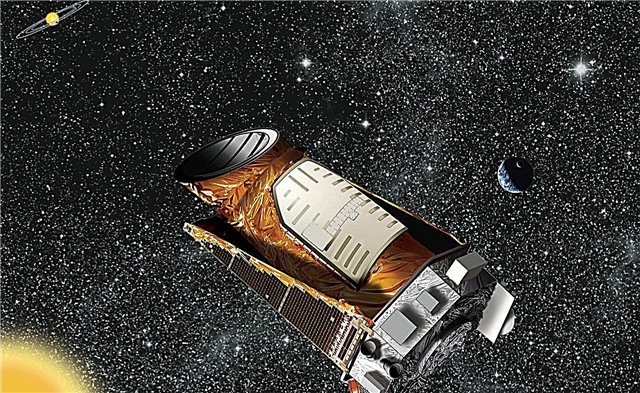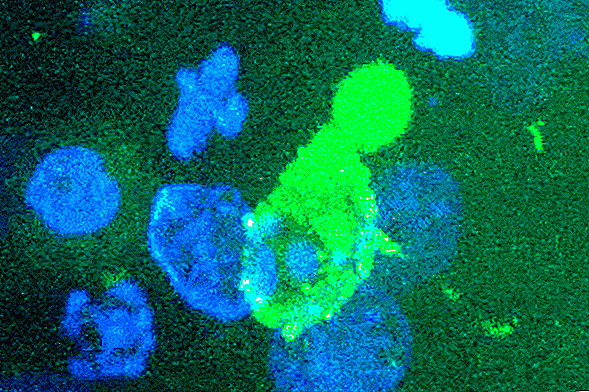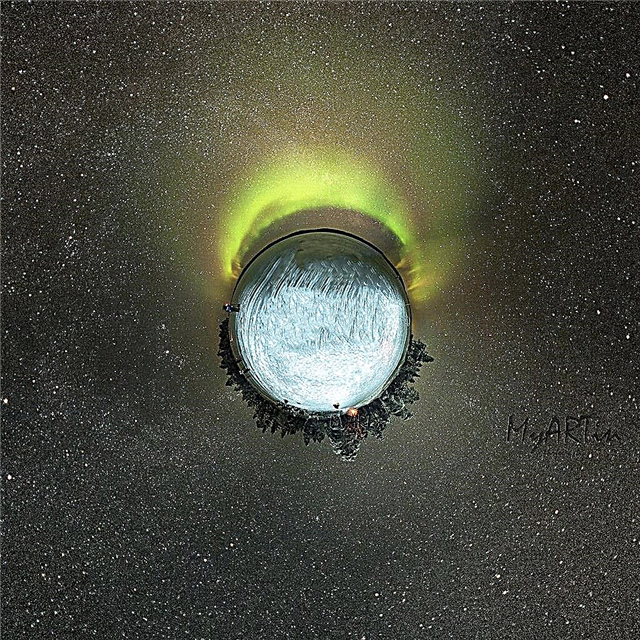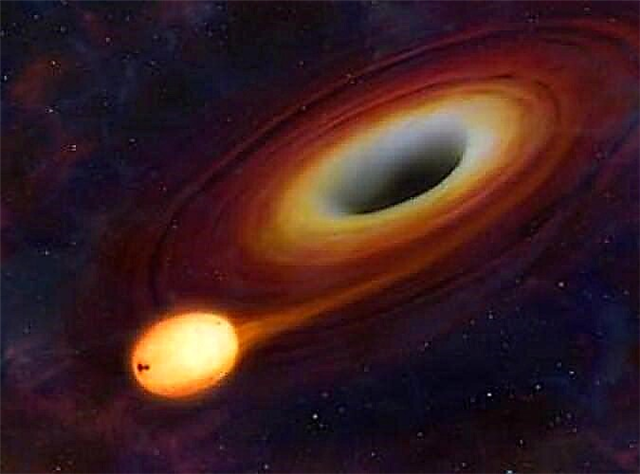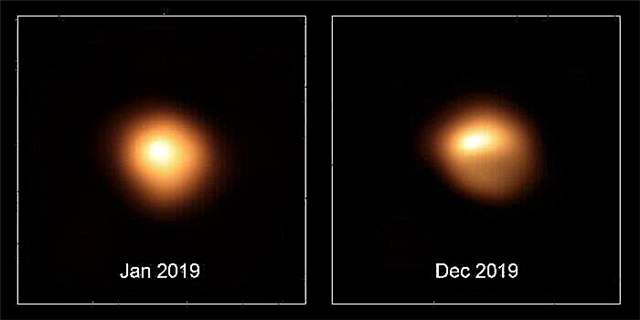Sebuah kisah bertahun-tahun antara pelari jarak menengah dan badan pengatur olahraganya mungkin mendekati sesuatu yang menyerupai kesimpulan.
Pada tahun 2018, Asosiasi Federasi Atletik Internasional mendikte bahwa pelari wanita dengan tingkat testosteron tinggi yang terjadi secara alami dan "perbedaan perkembangan jenis kelamin" tertentu harus menurunkan testosteron mereka untuk bersaing dalam acara yang berkisar 400 meter hingga satu mil.
Juara Olimpiade dua kali Caster Semenya menantang kebijakan 2018. Menurutnya, itu diskriminatif karena tidak memiliki landasan ilmiah dan melakukan "kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap atlet wanita yang terkena dampak."
Tetapi pada 1 Mei, dalam sebuah pukulan ke Semenya dan sejumlah wanita lain yang tak terhitung, Pengadilan Arbitrase Olahraga menegakkan peraturan. Kebijakan ini sekarang mulai berlaku pada 8 Mei
Sebagai seorang sarjana yang mempelajari olahraga wanita, saya telah mengikuti kisah ini dengan cermat. Inti dari konflik adalah bagaimana mendefinisikan "kewanitaan" untuk tujuan kompetisi atletik. Karena olahraga dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, kriteria apa - jika ada - yang harus kita gunakan untuk membedakan perempuan dari laki-laki?
Bagaimana kita sampai di sini
Pemantauan testosteron adalah versi terbaru dari "tes seks" dalam olahraga wanita, sebuah praktik yang dimulai pada 1930-an.
Pada abad ke-21, sebagian besar pengujian sistematis telah dihentikan, kecuali seseorang "menantang" jenis kelamin atlet wanita. Ini terjadi pada Semenya di Kejuaraan Dunia Track and Field 2009. Seseorang rupanya mengeluarkan tantangan semacam itu dan pers menangkapnya. Asosiasi Federasi Atletik Internasional membenarkan bahwa dia sedang menjalani prosedur "verifikasi gender", tepat sebelum dia meraih kemenangan dalam lomba 800 meter.
Meskipun hasil tesnya tidak pernah dipublikasikan, IAAF kemudian mengeluarkan kebijakan baru untuk wanita dengan hiperandrogenisme, atau testosteron tinggi. Dengan alasan bahwa testosteron yang tinggi memberi atlet ini keuntungan yang tidak adil, atlet wanita yang hiperandrogenik memiliki dua pilihan: menekan testosteron mereka atau keluar dari olahraga.
Pelari cepat India Dutee Chand menolak untuk melakukan keduanya. Pada tahun 2014, Otoritas Olahraga India mendiagnosisnya sebagai hiperandrogenik dan mendiskualifikasi dirinya dari kompetisi. Chand menantang bahwa diskualifikasi di Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga, di mana para hakim memutuskan IAAF memiliki "bukti yang tidak cukup" untuk menegakkan kebijakannya. Keputusan memberi organisasi dua tahun untuk menemukan bukti yang terkait peningkatan kinerja dengan kadar testosteron yang tinggi secara alami. Jika tidak, kebijakan tersebut akan dibatalkan.
Ketika tenggat waktu 2017 semakin dekat, para peneliti yang berafiliasi dengan IAAF menerbitkan sebuah penelitian yang mengklaim wanita dengan testosteron tinggi memiliki kinerja sebanyak 3% lebih baik daripada mereka yang memiliki testosteron lebih rendah dalam beberapa acara.
Tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengekspos kelemahan metodologis penelitian ini, organisasi itu terus maju dengan peraturannya, mendorong tantangan Semenya.
Diskriminasi 'Diperlukan'?
Meskipun menolak klaim Semenya, Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga mengakui bahwa peraturan itu "diskriminatif" tetapi "perlu" untuk menjaga "integritas atletik wanita." Peraturan itu juga diskriminatif, anggota panel mencatat, karena mereka "tidak mengenakan batasan yang setara pada atlet pria."
Ini adalah sesuatu yang dibebankan oleh para kritikus kebijakan sejak awal.
Tidak ada yang peduli dengan atlet pria dengan testosteron tinggi yang terjadi secara alami. Mengambil hormon dari persamaan, ada sejumlah keuntungan biologis yang dinikmati beberapa atlet daripada yang lain. Pemain ski Nordik Eero Mäntyranta, misalnya, memiliki kondisi genetik yang menyebabkan produksi berlebihan sel darah merah, memberinya keuntungan dalam peristiwa ketahanan. Tubuh renang Michael Phelps yang unik dan berbentuk optimal memungkinkannya menembus air dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Tidak ada yang menyarankan orang-orang ini untuk memberangus aset mereka.
Ini karena kami tidak membagi olahraga ke dalam kategori berdasarkan pada hemoglobin atau ukuran kaki, terlepas dari kelebihan yang diberikan masing-masing.
Kami, bagaimanapun, mengukir olahraga ke dalam kategori pria dan wanita, dan untuk alasan yang baik. Studi menunjukkan bahwa atlet pria elit cenderung mengungguli atlet wanita elit sekitar 10%. Memisahkan pria dan wanita dalam sebagian besar olahraga elit memberi perempuan lebih banyak peluang untuk bersaing dan berhasil.
Di sinilah rumit. Jika kita bersikeras pemisahan seksual dalam olahraga, bagaimana kita memutuskan siapa wanita dan siapa pria? Apakah kriteria tersebut mempengaruhi kinerja olahraga? Dan apa yang terjadi ketika atlet tidak cocok dengan definisi olahraga tentang kewanitaan?
Inilah tepatnya yang berusaha ditangani oleh peraturan baru, meskipun dengan cara yang canggung dan membingungkan. Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk wanita yang secara hukum diakui sebagai wanita tetapi yang didiagnosis dengan perbedaan spesifik kelainan seks dan memiliki kadar testosteron fungsional yang tinggi. IAAF menjelaskan bahwa gangguan ini melibatkan kromosom seks khas pria dan adanya testis atau perkembangan testis. Ambang batas untuk testosteron wanita di bawah kisaran pria "normal" tetapi lebih dari dua kali lebih tinggi dari batas atas kisaran wanita "normal".
Semenya dan para pendukungnya berpendapat bahwa karena perempuan yang terkena dampak kebijakan, pada kenyataannya, perempuan, mereka harus diizinkan untuk bersaing tanpa batasan.
"Aku hanya ingin berlari secara alami, seperti aku dilahirkan," katanya. "Tidak adil kalau aku diberitahu aku harus berubah."
Perlu dicatat bahwa meskipun Semenya adalah atlet top di kelasnya, waktunya tidak mendekati masa pelari pria elit - meskipun diduga memiliki "tingkat pria" testosteron.
Hak olahraga versus hak asasi manusia
Kontroversi ini telah memecah aktivis untuk hak olah raga dan HAM.
IAAF menganggap olahraga wanita sebagai "kelas yang dilindungi" dan bersikeras bahwa itu harus "menempatkan kondisi" pada kategori wanita untuk "untuk memastikan persaingan yang adil dan bermakna."
Aktivis HAM tidak setuju. Jika seorang atlet secara hukum adalah seorang wanita, itu sudah cukup. Bahkan, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa peraturan baru "mungkin tidak sesuai dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional." Mengutip pernyataan para ilmuwan dan ahli bioetika yang terhormat, dewan tersebut mengkritik "kurangnya bukti yang sah dan dapat dibenarkan untuk peraturan tersebut." Dengan kata lain, tidak ada korelasi yang konklusif dan tidak dapat dibantah antara testosteron alami yang tinggi dan kinerja yang lebih baik. Tanpa bukti seperti itu, mereka berpendapat, peraturan IAAF seharusnya tidak ditegakkan.
Anggota panel Pengadilan Arbitrase mencatat bahwa mereka khawatir tentang bagaimana peraturan IAAF akan diterapkan secara praktis. Selain itu, IAAF menganggap peraturan sebagai "dokumen hidup," yang berarti bahwa ia dapat dan mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu.
Apakah batasan testosteron akan meluas ke acara lintasan dan lapangan tambahan?
Sementara itu, Komite Olimpiade Internasional dilaporkan bekerja pada pedoman untuk membantu federasi internasional menyusun kebijakan mereka sendiri tentang "identitas gender dan karakteristik seks." Dengan kata lain, kita dapat mengharapkan untuk melihat kebijakan yang mirip dengan IAAF di olahraga lainnya.
Semenya memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding atas putusan arbitrase ke Pengadilan Federal Swiss. Jika banding ini gagal, dia dan banyak wanita lain harus mengurangi testosteron mereka, mungkin dengan obat-obatan, untuk tetap bersaing dalam acara-acara wanita. Apa yang akan dilakukan terhadap tubuh mereka? Ke olahraga? Untuk masalah keadilan dan hak asasi manusia?
Keputusan Pengadilan Arbitrase hanyalah satu langkah dalam apa yang tampaknya menjadi estafet yang tidak pernah berakhir dan mungkin sia-sia untuk membangun "keadilan" dalam olahraga wanita.
Jaime Schultz, Associate Professor Kinesiology, Pennsylvania State University.